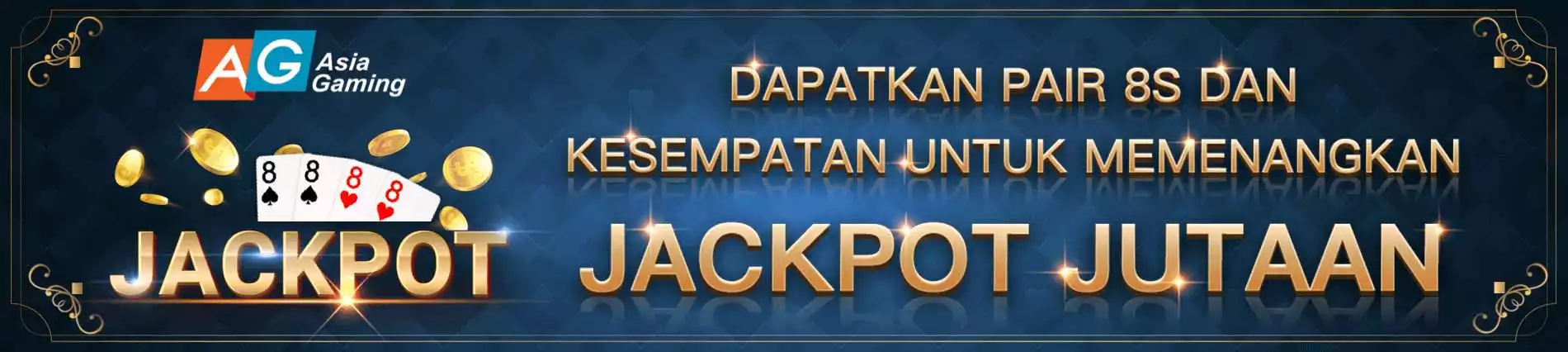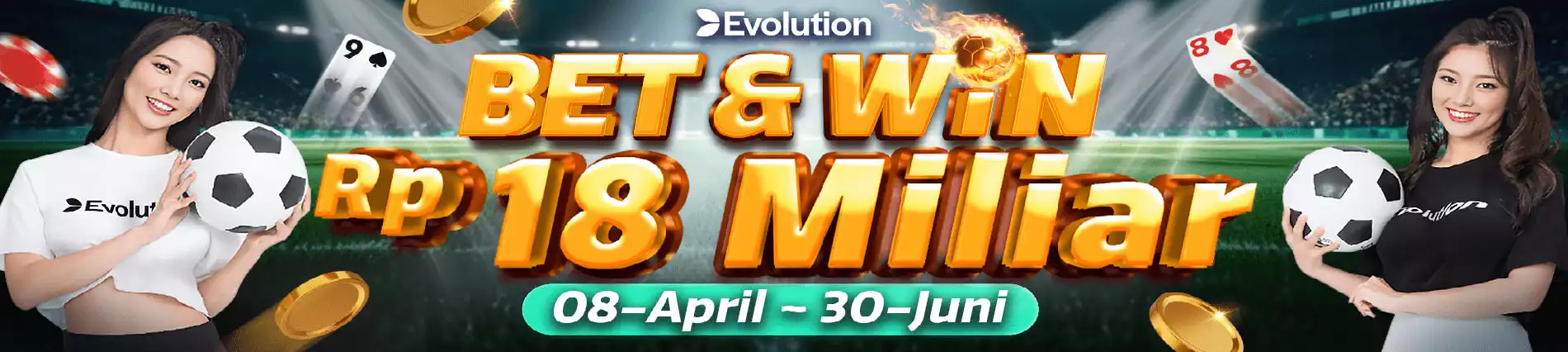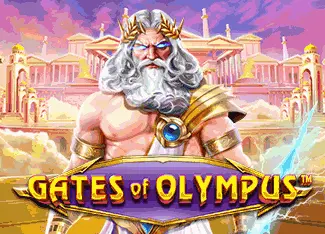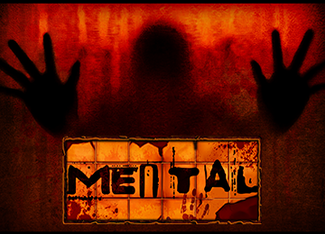IDR
Layanan Customer
Layanan Product

Permainan Terlengkap dalam seluruh platform
Lisensi Game

lisensi Resmi & Aman oleh PAGCOR
Layanan Member
Tambah Dana
Waktu
Menit
WITHDRAW
Waktu
Menit
Sistem Pembayaran

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
RAJINSLOT Hot Situs Game Keren Best Quality
RAJINSLOT Hot Situs Game Keren Best Quality
Rajinslot adalah situs hot dengan ragam game keren seru best quality serta pelayanan terbaik resmi dan terpercaya tersedia didalamnya. Sistem layanan terbaik dari customer service siap melayani 24jam nonstop khusus untuk kalian. Serta tentunya banyaknya game online bisa dirasakan setiap hari kapan saja dan dimana saja, dengan online cukup menggunakan satu akun untuk memainkan semua permainannya.